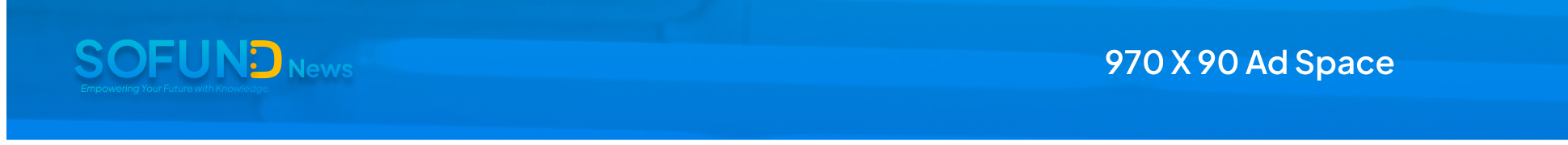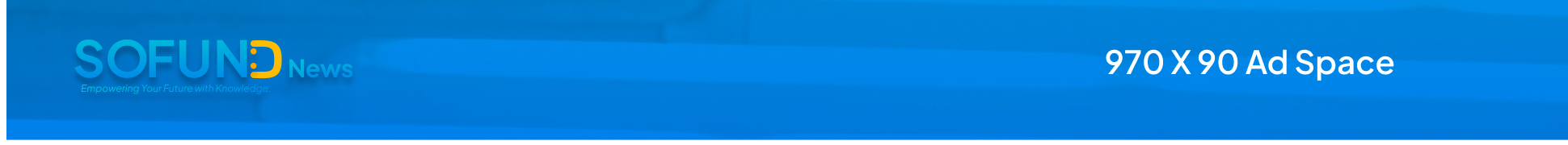AI dan Iklim: Antara Harapan Hijau dan Jejak Karbon Digital
Jakarta, Sofund.news – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Teknologi ini bukan hanya alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, melainkan telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di era digital ini, AI telah digunakan untuk menciptakan konten, menghasilkan ide, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga berperan sebagai pendamping interaktif dalam keseharian. Namun, seiring dunia menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim, kehadiran AI membawa babak baru: mampukah teknologi ini menjadi solusi atau justru beban tambahan bagi bumi?
Lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian ternama seperti Cambridge University dan Oxford University kini telah memanfaatkan AI dalam studi dan aksi iklim. Di Cambridge, teknologi AI digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemodelan iklim dan perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan. Di Oxford, para peneliti mengembangkan sistem kecerdasan buatan guna memantau dan mengevaluasi aksi-aksi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, menjadikannya lebih transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, raksasa teknologi dunia seperti Google secara terbuka mendukung pengembangan alat berbasis AI yang berorientasi pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim global.
Meskipun AI menjanjikan banyak manfaat, muncul pula kekhawatiran serius dari kalangan ilmuwan dan pemerhati lingkungan. Salah satu isu terbesar yang menjadi sorotan adalah konsumsi energi AI yang sangat besar. Menurut laporan dari International Energy Agency (IEA), permintaan energi yang dihasilkan oleh teknologi ini meningkat pesat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan daya yang tinggi untuk menjalankan dan melatih model bahasa berskala besar yang merupakan inti dari sistem AI. Ribuan server bekerja secara simultan di pusat-pusat data yang tersebar di seluruh dunia untuk menggerakkan teknologi ini.
AS menjadi negara dengan jumlah pusat data terbanyak, yaitu sekitar 5.381 fasilitas atau 40 persen dari total pusat data global. Sementara negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, India, Australia, Prancis, dan Belanda juga memainkan peran penting dalam infrastruktur ini. Diperkirakan pada tahun 2030, permintaan listrik dari pusat data akan mencapai 945 terawatt jam (TWh) angka yang bahkan melampaui total konsumsi listrik negara sekelas Jepang. Fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi AI terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) bisa menjadi signifikan bila tidak dikendalikan dengan bijak.
Salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Machine Learning mengungkapkan bahwa pelatihan model AI populer seperti ChatGPT dari OpenAI membutuhkan sekitar 1.287 megawatt jam (MWh) energi listrik. Konsumsi energi sebesar ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang setara dengan 80 kali penerbangan jarak pendek di Eropa. Hal ini menjadi alarm bagi komunitas global bahwa AI tidaklah ‘ramah iklim’ secara otomatis. Noman Bashir, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), menegaskan bahwa pelatihan AI generatif membutuhkan energi tujuh hingga delapan kali lipat dibandingkan proses komputasi biasa. Apalagi, ketika AI digunakan dalam konteks yang lebih berat seperti pemrosesan video, gambar, dan audio, kebutuhan energinya semakin membengkak.
Namun, tidak semua pihak melihat AI sebagai ancaman bagi iklim. IEA menyatakan bahwa meski konsumsi listrik pusat data meningkat, kontribusinya terhadap total emisi global masih tergolong kecil sekitar 1,5 persen. Bahkan, bila digunakan secara bijak, AI justru dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi emisi di sektor lain. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi energi di sektor transportasi, industri, dan agrikultur. Potensi ini disebutkan dalam laporan IEA yang memperkirakan bahwa adopsi AI secara luas dapat memangkas emisi global hingga lima persen pada tahun 2035. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat bantu untuk mengimbangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pusat data itu sendiri.
Dalam skenario yang lebih positif, AI dapat mempercepat transisi menuju energi bersih. Beberapa aplikasi AI sudah digunakan untuk manajemen jaringan listrik yang lebih cerdas, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, serta menurunkan biaya teknologi rendah karbon. Dengan peran ini, AI menjadi katalis dalam upaya global untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan. Namun, IEA juga menekankan bahwa saat ini belum ada jaminan bahwa aplikasi-aplikasi AI ini akan diadopsi secara luas dan konsisten di seluruh dunia. Potensi AI untuk menebus jejak karbonnya sendiri hanya akan tercapai jika implementasinya benar-benar meluas dan strategis.
Meski demikian, kita tetap perlu realistis. Karbon dioksida yang sudah dilepaskan ke atmosfer akan tetap berada di sana selama ratusan tahun. Maka dari itu, meskipun AI nantinya dapat mengurangi emisi lebih banyak daripada yang dihasilkannya, ia tidak serta-merta dapat menghapus dampak lingkungan yang sudah terjadi akibat operasionalnya. Dalam konteks ini, AI tidak bisa diposisikan sebagai ‘penebus sempurna’ bagi krisis iklim. Ia hanyalah satu dari sekian banyak alat yang bisa membantu manusia dalam perjuangan besar mengatasi perubahan iklim.
Laporan IEA dengan tegas menyimpulkan bahwa manfaat AI terhadap iklim sangat bergantung pada bagaimana dan seberapa luas teknologi ini digunakan. Jika diimplementasikan dengan cermat, AI bisa menjadi pelopor efisiensi dan solusi iklim. Namun, bila tidak dikendalikan, ia justru bisa memperparah masalah emisi global. Dunia membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta menerapkan teknologi AI, agar harapan besar terhadapnya tidak berubah menjadi beban baru bagi planet ini. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
AI dan Iklim: Antara Harapan Hijau dan Jejak Karbon Digital
Jakarta, Sofund.news – Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Teknologi ini bukan hanya alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, melainkan telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di era digital ini, AI telah digunakan untuk menciptakan konten, menghasilkan ide, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga berperan sebagai pendamping interaktif dalam keseharian. Namun, seiring dunia menghadapi tantangan besar berupa krisis iklim, kehadiran AI membawa babak baru: mampukah teknologi ini menjadi solusi atau justru beban tambahan bagi bumi?
Lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian ternama seperti Cambridge University dan Oxford University kini telah memanfaatkan AI dalam studi dan aksi iklim. Di Cambridge, teknologi AI digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemodelan iklim dan perencanaan tata guna lahan yang berkelanjutan. Di Oxford, para peneliti mengembangkan sistem kecerdasan buatan guna memantau dan mengevaluasi aksi-aksi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, menjadikannya lebih transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu, raksasa teknologi dunia seperti Google secara terbuka mendukung pengembangan alat berbasis AI yang berorientasi pada peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim global.
Meskipun AI menjanjikan banyak manfaat, muncul pula kekhawatiran serius dari kalangan ilmuwan dan pemerhati lingkungan. Salah satu isu terbesar yang menjadi sorotan adalah konsumsi energi AI yang sangat besar. Menurut laporan dari International Energy Agency (IEA), permintaan energi yang dihasilkan oleh teknologi ini meningkat pesat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan daya yang tinggi untuk menjalankan dan melatih model bahasa berskala besar yang merupakan inti dari sistem AI. Ribuan server bekerja secara simultan di pusat-pusat data yang tersebar di seluruh dunia untuk menggerakkan teknologi ini.
AS menjadi negara dengan jumlah pusat data terbanyak, yaitu sekitar 5.381 fasilitas atau 40 persen dari total pusat data global. Sementara negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, India, Australia, Prancis, dan Belanda juga memainkan peran penting dalam infrastruktur ini. Diperkirakan pada tahun 2030, permintaan listrik dari pusat data akan mencapai 945 terawatt jam (TWh) angka yang bahkan melampaui total konsumsi listrik negara sekelas Jepang. Fakta ini menunjukkan bahwa kontribusi AI terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) bisa menjadi signifikan bila tidak dikendalikan dengan bijak.
Salah satu penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Machine Learning mengungkapkan bahwa pelatihan model AI populer seperti ChatGPT dari OpenAI membutuhkan sekitar 1.287 megawatt jam (MWh) energi listrik. Konsumsi energi sebesar ini menghasilkan emisi karbon dioksida yang setara dengan 80 kali penerbangan jarak pendek di Eropa. Hal ini menjadi alarm bagi komunitas global bahwa AI tidaklah ‘ramah iklim’ secara otomatis. Noman Bashir, peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), menegaskan bahwa pelatihan AI generatif membutuhkan energi tujuh hingga delapan kali lipat dibandingkan proses komputasi biasa. Apalagi, ketika AI digunakan dalam konteks yang lebih berat seperti pemrosesan video, gambar, dan audio, kebutuhan energinya semakin membengkak.
Namun, tidak semua pihak melihat AI sebagai ancaman bagi iklim. IEA menyatakan bahwa meski konsumsi listrik pusat data meningkat, kontribusinya terhadap total emisi global masih tergolong kecil sekitar 1,5 persen. Bahkan, bila digunakan secara bijak, AI justru dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi emisi di sektor lain. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi energi di sektor transportasi, industri, dan agrikultur. Potensi ini disebutkan dalam laporan IEA yang memperkirakan bahwa adopsi AI secara luas dapat memangkas emisi global hingga lima persen pada tahun 2035. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat bantu untuk mengimbangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pusat data itu sendiri.
Dalam skenario yang lebih positif, AI dapat mempercepat transisi menuju energi bersih. Beberapa aplikasi AI sudah digunakan untuk manajemen jaringan listrik yang lebih cerdas, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, serta menurunkan biaya teknologi rendah karbon. Dengan peran ini, AI menjadi katalis dalam upaya global untuk membangun sistem energi yang lebih berkelanjutan. Namun, IEA juga menekankan bahwa saat ini belum ada jaminan bahwa aplikasi-aplikasi AI ini akan diadopsi secara luas dan konsisten di seluruh dunia. Potensi AI untuk menebus jejak karbonnya sendiri hanya akan tercapai jika implementasinya benar-benar meluas dan strategis.
Meski demikian, kita tetap perlu realistis. Karbon dioksida yang sudah dilepaskan ke atmosfer akan tetap berada di sana selama ratusan tahun. Maka dari itu, meskipun AI nantinya dapat mengurangi emisi lebih banyak daripada yang dihasilkannya, ia tidak serta-merta dapat menghapus dampak lingkungan yang sudah terjadi akibat operasionalnya. Dalam konteks ini, AI tidak bisa diposisikan sebagai ‘penebus sempurna’ bagi krisis iklim. Ia hanyalah satu dari sekian banyak alat yang bisa membantu manusia dalam perjuangan besar mengatasi perubahan iklim.
Laporan IEA dengan tegas menyimpulkan bahwa manfaat AI terhadap iklim sangat bergantung pada bagaimana dan seberapa luas teknologi ini digunakan. Jika diimplementasikan dengan cermat, AI bisa menjadi pelopor efisiensi dan solusi iklim. Namun, bila tidak dikendalikan, ia justru bisa memperparah masalah emisi global. Dunia membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan serta menerapkan teknologi AI, agar harapan besar terhadapnya tidak berubah menjadi beban baru bagi planet ini. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)