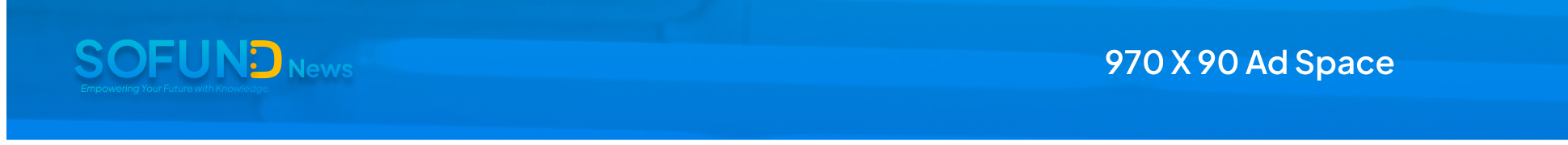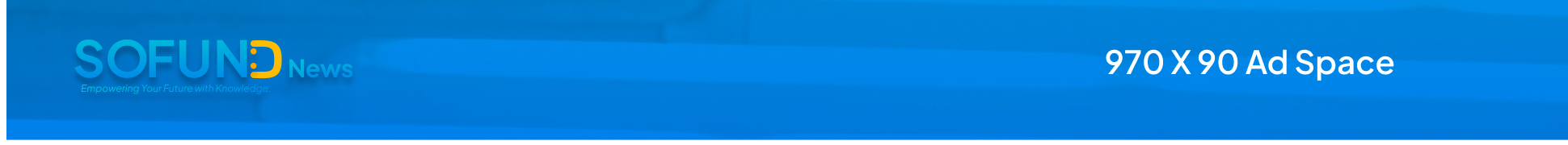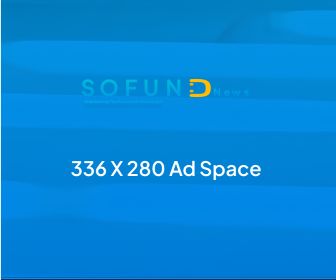Hari Bumi, Cemas pada Krisis Iklim? Ini Cara Mengubahnya Jadi Aksi
Jakarta, Sofund.news – Setiap kali mendengar berita tentang banjir bandang, kebakaran hutan, suhu ekstrem, atau mencairnya es di kutub, barangkali kamu akan merasa dada sedikit sesak, seolah-olah sedang menyaksikan sebuah bencana yang menghampiri perlahan namun pasti. Perasaan itu—cemas, takut, khawatir akan masa depan Bumi—bukanlah hal yang aneh. Justru, itu pertanda bahwa kamu peduli. Tapi bagaimana jika perasaan itu berubah menjadi kecemasan yang berlebihan hingga mengganggu ketenangan dan kesehatan mental? Di sinilah kita mengenal istilah eco-anxiety atau kecemasan lingkungan.
Fenomena ini mulai menjadi sorotan karena semakin banyak orang, terutama dari kalangan muda, merasa dilanda kegelisahan mendalam terhadap kondisi lingkungan. Menyaksikan kerusakan yang terus terjadi membuat mereka merasa putus asa, frustrasi, bahkan tidak berdaya. Dalam beberapa kasus, kecemasan ini berkembang menjadi gangguan serius, seperti serangan panik, kesulitan tidur, dan hilangnya fokus. Tidak sedikit yang kemudian kehilangan semangat untuk menjalani hidup karena merasa semua usaha akan sia-sia jika Bumi tetap menuju kehancuran.
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah generasi Z. Berdasarkan berbagai studi, generasi ini paling sering mengalami eco-anxiety dibanding kelompok usia lain. Mereka tumbuh di tengah perubahan iklim yang kian nyata: musim yang tak menentu, bencana yang datang silih berganti, serta isu-isu lingkungan yang memenuhi ruang digital. Generasi ini tak hanya lebih terpapar, tapi juga lebih sadar akan apa yang terjadi—dan itu membawa beban emosional tersendiri.
Namun, seperti halnya bentuk kecemasan lainnya, eco-anxiety bisa dikelola. Kita tidak harus menyerah atau membiarkan rasa cemas mendikte hidup kita. Ada sejumlah cara yang dapat membantu mengalihkan kecemasan menjadi energi yang lebih produktif dan positif. Salah satunya adalah mengatur paparan informasi. Informasi yang kita konsumsi setiap hari sangat memengaruhi kondisi psikologis kita. Terlalu banyak membaca berita buruk atau konten negatif tentang bencana bisa memperburuk kecemasan. Sebaliknya, mencari konten yang memberi solusi atau harapan bisa memberi kekuatan mental. Mengikuti akun media sosial yang berisi cerita-cerita perubahan, aksi komunitas, atau proyek lingkungan yang berhasil bisa membantu kita merasa bahwa perubahan itu mungkin.
Selain itu, bergabung dalam komunitas yang memiliki visi serupa bisa menjadi pelipur lara. Komunitas lingkungan tidak hanya memberi ruang untuk berbagi keresahan, tapi juga menciptakan rasa kebersamaan. Ketika kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam kepedulian ini, kecemasan terasa lebih ringan. Lebih dari itu, komunitas bisa menjadi tempat memulai aksi nyata. Tak perlu langsung menjadi aktivis besar, cukup mulai dari partisipasi kecil seperti mengikuti kampanye daring, membuat konten edukatif, atau ikut dalam kegiatan seperti penanaman pohon atau bersih-bersih sungai.
Sebuah studi menunjukkan bahwa aksi nyata—sekecil apa pun—mampu membangun rasa percaya diri individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ini yang disebut dengan self and community efficacy. Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas positif, semakin kuat keyakinannya bahwa perubahan bisa terjadi.
Kisah nyata dari Bendungan Katulampa di Kota Bogor bisa menjadi contoh bagaimana partisipasi anak muda sangat penting. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa para pemuda di sekitar bendungan ini sebenarnya memiliki banyak ide untuk menjaga air dan mengatasi risiko banjir. Sayangnya, mereka tidak tahu ke mana harus menyuarakan aspirasi itu. Tim peneliti kemudian membantu menjembatani komunikasi mereka dengan pemerintah kota, termasuk dengan wali kota saat itu, Bima Arya. Hasilnya, lahirlah rekomendasi pelatihan pengelolaan air dan pemanenan air hujan. Dari yang semula hanya keresahan, para pemuda itu kini punya peran nyata dalam menjaga lingkungan.
Sayangnya, saluran resmi untuk partisipasi generasi muda dalam kebijakan lingkungan masih terbatas. Forum-formal yang ada sering kali tidak ramah bagi gaya komunikasi mereka. Hal ini bisa memunculkan perasaan tidak didengar, tidak dipercaya, bahkan apatis. Di sinilah pentingnya institusi pendidikan dan media sosial untuk mengambil peran.
Kampus, sebagai tempat berkumpulnya anak muda, memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran lingkungan. Universitas bisa mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam mata kuliah, proyek mahasiswa, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, di Universitas Gadjah Mada, praktikum teknik lingkungan diselaraskan dengan kegiatan nyata seperti aksi bersih sungai, sehingga mahasiswa tak hanya belajar teori tapi juga langsung berkontribusi ke masyarakat.
Sementara itu, media sosial menjadi ruang paling dinamis tempat anak muda berkumpul, bersuara, dan membentuk opini. Narasi yang kuat dan storytelling yang inspiratif bisa menjadi pemantik perubahan sosial. Akun seperti @pandawaragroup dan @aeshnina menjadi bukti kekuatan medsos. Pandawara membersihkan sungai-sungai kotor dan mengundang perhatian publik secara luas. Nina, gadis muda yang berani bicara di forum-forum internasional tentang krisis plastik, menunjukkan bahwa suara anak muda bisa menggema hingga ke level tertinggi.
Meski hasil dari kampanye tersebut belum selalu terlihat secara konkret, tetapi konsistensi dan keberanian mereka menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil. Kamu pun bisa memulainya sekarang. Tak perlu menunggu jadi aktivis, cukup dengan mengganti kebiasaan, mengurangi plastik, menyebarkan konten positif, atau mulai memilah sampah di rumah.
Kecemasan lingkungan adalah tanda bahwa kamu peduli. Tapi jangan biarkan rasa cemas itu membuatmu lumpuh. Alihkan keresahan menjadi aksi. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, bisa menjadi bagian dari solusi besar untuk masa depan Bumi. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
Hari Bumi, Cemas pada Krisis Iklim? Ini Cara Mengubahnya Jadi Aksi
Jakarta, Sofund.news – Setiap kali mendengar berita tentang banjir bandang, kebakaran hutan, suhu ekstrem, atau mencairnya es di kutub, barangkali kamu akan merasa dada sedikit sesak, seolah-olah sedang menyaksikan sebuah bencana yang menghampiri perlahan namun pasti. Perasaan itu—cemas, takut, khawatir akan masa depan Bumi—bukanlah hal yang aneh. Justru, itu pertanda bahwa kamu peduli. Tapi bagaimana jika perasaan itu berubah menjadi kecemasan yang berlebihan hingga mengganggu ketenangan dan kesehatan mental? Di sinilah kita mengenal istilah eco-anxiety atau kecemasan lingkungan.
Fenomena ini mulai menjadi sorotan karena semakin banyak orang, terutama dari kalangan muda, merasa dilanda kegelisahan mendalam terhadap kondisi lingkungan. Menyaksikan kerusakan yang terus terjadi membuat mereka merasa putus asa, frustrasi, bahkan tidak berdaya. Dalam beberapa kasus, kecemasan ini berkembang menjadi gangguan serius, seperti serangan panik, kesulitan tidur, dan hilangnya fokus. Tidak sedikit yang kemudian kehilangan semangat untuk menjalani hidup karena merasa semua usaha akan sia-sia jika Bumi tetap menuju kehancuran.
Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah generasi Z. Berdasarkan berbagai studi, generasi ini paling sering mengalami eco-anxiety dibanding kelompok usia lain. Mereka tumbuh di tengah perubahan iklim yang kian nyata: musim yang tak menentu, bencana yang datang silih berganti, serta isu-isu lingkungan yang memenuhi ruang digital. Generasi ini tak hanya lebih terpapar, tapi juga lebih sadar akan apa yang terjadi—dan itu membawa beban emosional tersendiri.
Namun, seperti halnya bentuk kecemasan lainnya, eco-anxiety bisa dikelola. Kita tidak harus menyerah atau membiarkan rasa cemas mendikte hidup kita. Ada sejumlah cara yang dapat membantu mengalihkan kecemasan menjadi energi yang lebih produktif dan positif. Salah satunya adalah mengatur paparan informasi. Informasi yang kita konsumsi setiap hari sangat memengaruhi kondisi psikologis kita. Terlalu banyak membaca berita buruk atau konten negatif tentang bencana bisa memperburuk kecemasan. Sebaliknya, mencari konten yang memberi solusi atau harapan bisa memberi kekuatan mental. Mengikuti akun media sosial yang berisi cerita-cerita perubahan, aksi komunitas, atau proyek lingkungan yang berhasil bisa membantu kita merasa bahwa perubahan itu mungkin.
Selain itu, bergabung dalam komunitas yang memiliki visi serupa bisa menjadi pelipur lara. Komunitas lingkungan tidak hanya memberi ruang untuk berbagi keresahan, tapi juga menciptakan rasa kebersamaan. Ketika kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam kepedulian ini, kecemasan terasa lebih ringan. Lebih dari itu, komunitas bisa menjadi tempat memulai aksi nyata. Tak perlu langsung menjadi aktivis besar, cukup mulai dari partisipasi kecil seperti mengikuti kampanye daring, membuat konten edukatif, atau ikut dalam kegiatan seperti penanaman pohon atau bersih-bersih sungai.
Sebuah studi menunjukkan bahwa aksi nyata—sekecil apa pun—mampu membangun rasa percaya diri individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan lingkungan. Ini yang disebut dengan self and community efficacy. Semakin sering seseorang terlibat dalam aktivitas positif, semakin kuat keyakinannya bahwa perubahan bisa terjadi.
Kisah nyata dari Bendungan Katulampa di Kota Bogor bisa menjadi contoh bagaimana partisipasi anak muda sangat penting. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa para pemuda di sekitar bendungan ini sebenarnya memiliki banyak ide untuk menjaga air dan mengatasi risiko banjir. Sayangnya, mereka tidak tahu ke mana harus menyuarakan aspirasi itu. Tim peneliti kemudian membantu menjembatani komunikasi mereka dengan pemerintah kota, termasuk dengan wali kota saat itu, Bima Arya. Hasilnya, lahirlah rekomendasi pelatihan pengelolaan air dan pemanenan air hujan. Dari yang semula hanya keresahan, para pemuda itu kini punya peran nyata dalam menjaga lingkungan.
Sayangnya, saluran resmi untuk partisipasi generasi muda dalam kebijakan lingkungan masih terbatas. Forum-formal yang ada sering kali tidak ramah bagi gaya komunikasi mereka. Hal ini bisa memunculkan perasaan tidak didengar, tidak dipercaya, bahkan apatis. Di sinilah pentingnya institusi pendidikan dan media sosial untuk mengambil peran.
Kampus, sebagai tempat berkumpulnya anak muda, memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran lingkungan. Universitas bisa mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam mata kuliah, proyek mahasiswa, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, di Universitas Gadjah Mada, praktikum teknik lingkungan diselaraskan dengan kegiatan nyata seperti aksi bersih sungai, sehingga mahasiswa tak hanya belajar teori tapi juga langsung berkontribusi ke masyarakat.
Sementara itu, media sosial menjadi ruang paling dinamis tempat anak muda berkumpul, bersuara, dan membentuk opini. Narasi yang kuat dan storytelling yang inspiratif bisa menjadi pemantik perubahan sosial. Akun seperti @pandawaragroup dan @aeshnina menjadi bukti kekuatan medsos. Pandawara membersihkan sungai-sungai kotor dan mengundang perhatian publik secara luas. Nina, gadis muda yang berani bicara di forum-forum internasional tentang krisis plastik, menunjukkan bahwa suara anak muda bisa menggema hingga ke level tertinggi.
Meski hasil dari kampanye tersebut belum selalu terlihat secara konkret, tetapi konsistensi dan keberanian mereka menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil. Kamu pun bisa memulainya sekarang. Tak perlu menunggu jadi aktivis, cukup dengan mengganti kebiasaan, mengurangi plastik, menyebarkan konten positif, atau mulai memilah sampah di rumah.
Kecemasan lingkungan adalah tanda bahwa kamu peduli. Tapi jangan biarkan rasa cemas itu membuatmu lumpuh. Alihkan keresahan menjadi aksi. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, bisa menjadi bagian dari solusi besar untuk masa depan Bumi. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)