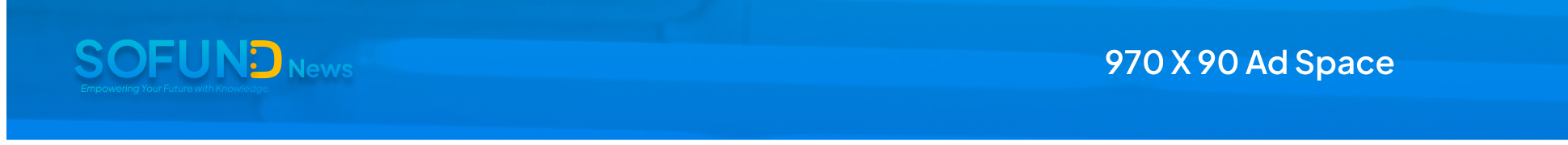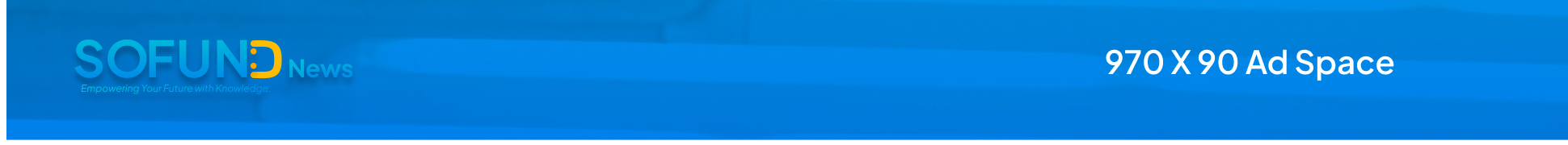Jerat Dunia Maya: Ketika Ideologi Incel dan Radikalisme Gender Mengintai Remaja
Jakarta, Sofund.news – Serial Netflix berjudul Adolescence baru-baru ini menjadi sorotan karena mengangkat tema yang tidak biasa dalam genre drama psikologis—yakni radikalisme gender dan ideologi incel. Cerita berfokus pada kehidupan Jamie, seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang sepintas tampak seperti anak kebanyakan. Ia menghabiskan waktu di kamar, bermain komputer, dan tampak tenang tanpa masalah berarti. Namun, semua berubah ketika rekaman kamera pengawas memperlihatkan Jamie melakukan tindakan mengerikan: membunuh teman sekolahnya, Katie, dengan sebilah pisau. Kejadian ini tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar: apa yang mendorong seorang anak muda melakukan tindakan sekejam itu?
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Jamie bukan sekadar pelaku kekerasan tanpa motif. Ia ternyata telah lama terpapar ideologi berbahaya yang berakar dari forum-forum online yang mewadahi radikalisme gender dan paham incel. Seorang psikolog anak yang terlibat dalam penanganan kasus Jamie menemukan bahwa ia terpengaruh oleh narasi-narasi ekstrem tentang peran gender, kebencian terhadap perempuan, dan tekanan maskulinitas.
Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, penting terlebih dahulu memahami dua konsep utama yang jadi pemicu cerita ini: radikalisme gender dan ideologi incel. Radikalisme gender merupakan pandangan ekstrem terhadap peran gender, mencakup konsep seperti maskulinitas toksik dan kebencian terhadap lawan jenis. Laki-laki yang memandang rendah perempuan, bahkan membenci mereka secara ekstrem, disebut sebagai misoginis. Sebaliknya, perempuan yang membenci laki-laki disebut misandris. Dalam masyarakat yang terpapar ideologi ini, laki-laki dipaksa mengikuti standar kaku yang mendefinisikan apa itu “laki-laki sejati”: kuat, tidak emosional, menolak pekerjaan domestik, dan harus gemar olahraga.
Sementara itu, ideologi incel singkatan dari involuntary celibate—merujuk pada individu atau kelompok, biasanya laki-laki, yang merasa berhak mendapatkan cinta dan seks, tetapi tidak berhasil meraihnya. Ketidakmampuan ini lalu dilampiaskan dalam bentuk kebencian terhadap perempuan dan masyarakat. Dalam makalah yang diterbitkan oleh Current Psychiatry Reports, disebutkan bahwa para incel cenderung menyalahkan perempuan atas penolakan yang mereka alami. Sementara studi lain yang terbit dalam jurnal Studies in Conflict & Terrorism menegaskan bahwa ideologi ini dapat berkembang menjadi glorifikasi kekerasan dan ekstremisme.
Dalam Adolescence, Jamie adalah potret nyata dari betapa berbahayanya dunia maya bagi remaja yang masih dalam tahap mencari jati diri. Ia merasa tidak cukup menarik, tidak populer, dan tidak memenuhi ekspektasi ayahnya yang menginginkannya jago olahraga. Ketika mencari tempat pelarian, ia menemukan forum daring bernama “Manosphere”. Di forum tersebut, Jamie merasa diterima, bahkan dipuji. Padahal, di situlah ia dicekoki pemikiran misoginis dan paham incel. Hasil akhirnya tragis: Katie menjadi korban kebencian yang dibentuk oleh paparan konten beracun.
Psikolog klinis anak dan remaja, Lydia Agnes Gultom, M.Psi., menegaskan pentingnya peran orangtua dalam mencegah paparan ideologi berbahaya kepada anak. Menurutnya, orangtua harus mulai melek digital dan menerapkan digital parenting. Dunia maya, kata Agnes, kini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari kehidupan anak yang memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Maka dari itu, orangtua perlu tahu aplikasi apa saja yang digunakan anak, bagaimana anak memakainya, dan konten seperti apa yang mereka konsumsi.
Tak kalah penting dari itu adalah komunikasi terbuka antara anak dan orangtua. Anak-anak harus merasa nyaman untuk bercerita, termasuk tentang pengalaman mereka di dunia maya, baik yang menyenangkan maupun yang membuat mereka bingung atau takut. Orangtua harus bisa menjadi tempat yang aman, bukan justru tempat anak merasa dihakimi. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi dalam dunia anak, termasuk paparan konten yang mereka terima.
Selain komunikasi, penting juga membahas batasan penggunaan media sosial dengan anak secara rasional. Bukan hanya membatasi durasi penggunaan, tetapi juga menjelaskan mengapa beberapa konten tidak pantas, dan mengapa aplikasi tertentu harus dihindari. Anak perlu tahu alasannya agar tidak sekadar patuh, tetapi paham dan bisa mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi informasi yang salah. Menurut Agnes, tanpa pelatihan berpikir kritis, anak-anak hanya akan menjadi konsumen pasif informasi yang mereka lihat.
Edukasi tentang kesetaraan gender juga menjadi pondasi penting. Anak-anak yang dibekali pemahaman tentang persamaan hak, peran, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, cenderung memiliki sikap yang lebih sehat terhadap lawan jenis maupun terhadap identitas gender mereka sendiri. Pemahaman ini akan menjadi filter alami ketika mereka bertemu dengan ideologi ekstrem seperti misogini atau maskulinitas toksik. Mereka akan bisa mempertanyakan konten yang salah, dan tidak langsung percaya.
Poin yang ditekankan Agnes adalah bahwa membangun pola pikir kritis pada anak merupakan bentuk perlindungan terbaik. Ketika anak tahu bahwa tidak semua yang dilihat di internet adalah benar, mereka tidak akan langsung menelan informasi mentah-mentah. Mereka akan bisa membedakan mana fakta, opini, dan propaganda. Inilah yang menjadi benteng utama ketika dunia maya mulai menyusupkan paham yang berbahaya.
Kisah dalam Adolescence menjadi peringatan penting bahwa bahaya ideologi ekstrem bisa menyelinap lewat layar komputer di kamar anak-anak. Jamie adalah peringatan tragis akan dampak dari keterasingan, kurangnya pendampingan, dan paparan konten destruktif. Untuk mencegah hal serupa, orangtua dan masyarakat harus bahu-membahu membekali generasi muda dengan pengetahuan, kepekaan, dan kemampuan berpikir kritis. Dunia maya memang tak bisa dihindari, tetapi anak-anak tak boleh dibiarkan menavigasinya sendirian. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
Jerat Dunia Maya: Ketika Ideologi Incel dan Radikalisme Gender Mengintai Remaja
Jakarta, Sofund.news – Serial Netflix berjudul Adolescence baru-baru ini menjadi sorotan karena mengangkat tema yang tidak biasa dalam genre drama psikologis—yakni radikalisme gender dan ideologi incel. Cerita berfokus pada kehidupan Jamie, seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun yang sepintas tampak seperti anak kebanyakan. Ia menghabiskan waktu di kamar, bermain komputer, dan tampak tenang tanpa masalah berarti. Namun, semua berubah ketika rekaman kamera pengawas memperlihatkan Jamie melakukan tindakan mengerikan: membunuh teman sekolahnya, Katie, dengan sebilah pisau. Kejadian ini tentu mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan besar: apa yang mendorong seorang anak muda melakukan tindakan sekejam itu?
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Jamie bukan sekadar pelaku kekerasan tanpa motif. Ia ternyata telah lama terpapar ideologi berbahaya yang berakar dari forum-forum online yang mewadahi radikalisme gender dan paham incel. Seorang psikolog anak yang terlibat dalam penanganan kasus Jamie menemukan bahwa ia terpengaruh oleh narasi-narasi ekstrem tentang peran gender, kebencian terhadap perempuan, dan tekanan maskulinitas.
Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, penting terlebih dahulu memahami dua konsep utama yang jadi pemicu cerita ini: radikalisme gender dan ideologi incel. Radikalisme gender merupakan pandangan ekstrem terhadap peran gender, mencakup konsep seperti maskulinitas toksik dan kebencian terhadap lawan jenis. Laki-laki yang memandang rendah perempuan, bahkan membenci mereka secara ekstrem, disebut sebagai misoginis. Sebaliknya, perempuan yang membenci laki-laki disebut misandris. Dalam masyarakat yang terpapar ideologi ini, laki-laki dipaksa mengikuti standar kaku yang mendefinisikan apa itu “laki-laki sejati”: kuat, tidak emosional, menolak pekerjaan domestik, dan harus gemar olahraga.
Sementara itu, ideologi incel singkatan dari involuntary celibate—merujuk pada individu atau kelompok, biasanya laki-laki, yang merasa berhak mendapatkan cinta dan seks, tetapi tidak berhasil meraihnya. Ketidakmampuan ini lalu dilampiaskan dalam bentuk kebencian terhadap perempuan dan masyarakat. Dalam makalah yang diterbitkan oleh Current Psychiatry Reports, disebutkan bahwa para incel cenderung menyalahkan perempuan atas penolakan yang mereka alami. Sementara studi lain yang terbit dalam jurnal Studies in Conflict & Terrorism menegaskan bahwa ideologi ini dapat berkembang menjadi glorifikasi kekerasan dan ekstremisme.
Dalam Adolescence, Jamie adalah potret nyata dari betapa berbahayanya dunia maya bagi remaja yang masih dalam tahap mencari jati diri. Ia merasa tidak cukup menarik, tidak populer, dan tidak memenuhi ekspektasi ayahnya yang menginginkannya jago olahraga. Ketika mencari tempat pelarian, ia menemukan forum daring bernama “Manosphere”. Di forum tersebut, Jamie merasa diterima, bahkan dipuji. Padahal, di situlah ia dicekoki pemikiran misoginis dan paham incel. Hasil akhirnya tragis: Katie menjadi korban kebencian yang dibentuk oleh paparan konten beracun.
Psikolog klinis anak dan remaja, Lydia Agnes Gultom, M.Psi., menegaskan pentingnya peran orangtua dalam mencegah paparan ideologi berbahaya kepada anak. Menurutnya, orangtua harus mulai melek digital dan menerapkan digital parenting. Dunia maya, kata Agnes, kini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari kehidupan anak yang memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Maka dari itu, orangtua perlu tahu aplikasi apa saja yang digunakan anak, bagaimana anak memakainya, dan konten seperti apa yang mereka konsumsi.
Tak kalah penting dari itu adalah komunikasi terbuka antara anak dan orangtua. Anak-anak harus merasa nyaman untuk bercerita, termasuk tentang pengalaman mereka di dunia maya, baik yang menyenangkan maupun yang membuat mereka bingung atau takut. Orangtua harus bisa menjadi tempat yang aman, bukan justru tempat anak merasa dihakimi. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memahami apa yang terjadi dalam dunia anak, termasuk paparan konten yang mereka terima.
Selain komunikasi, penting juga membahas batasan penggunaan media sosial dengan anak secara rasional. Bukan hanya membatasi durasi penggunaan, tetapi juga menjelaskan mengapa beberapa konten tidak pantas, dan mengapa aplikasi tertentu harus dihindari. Anak perlu tahu alasannya agar tidak sekadar patuh, tetapi paham dan bisa mengambil keputusan sendiri ketika menghadapi informasi yang salah. Menurut Agnes, tanpa pelatihan berpikir kritis, anak-anak hanya akan menjadi konsumen pasif informasi yang mereka lihat.
Edukasi tentang kesetaraan gender juga menjadi pondasi penting. Anak-anak yang dibekali pemahaman tentang persamaan hak, peran, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, cenderung memiliki sikap yang lebih sehat terhadap lawan jenis maupun terhadap identitas gender mereka sendiri. Pemahaman ini akan menjadi filter alami ketika mereka bertemu dengan ideologi ekstrem seperti misogini atau maskulinitas toksik. Mereka akan bisa mempertanyakan konten yang salah, dan tidak langsung percaya.
Poin yang ditekankan Agnes adalah bahwa membangun pola pikir kritis pada anak merupakan bentuk perlindungan terbaik. Ketika anak tahu bahwa tidak semua yang dilihat di internet adalah benar, mereka tidak akan langsung menelan informasi mentah-mentah. Mereka akan bisa membedakan mana fakta, opini, dan propaganda. Inilah yang menjadi benteng utama ketika dunia maya mulai menyusupkan paham yang berbahaya.
Kisah dalam Adolescence menjadi peringatan penting bahwa bahaya ideologi ekstrem bisa menyelinap lewat layar komputer di kamar anak-anak. Jamie adalah peringatan tragis akan dampak dari keterasingan, kurangnya pendampingan, dan paparan konten destruktif. Untuk mencegah hal serupa, orangtua dan masyarakat harus bahu-membahu membekali generasi muda dengan pengetahuan, kepekaan, dan kemampuan berpikir kritis. Dunia maya memang tak bisa dihindari, tetapi anak-anak tak boleh dibiarkan menavigasinya sendirian. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)