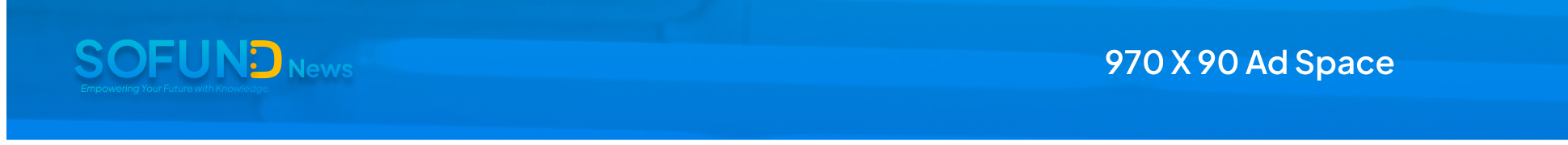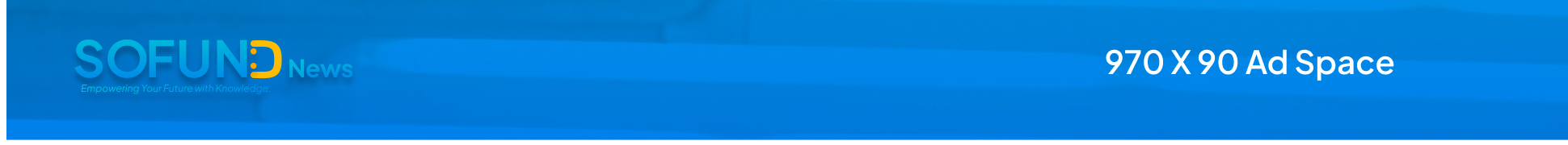Kembali ke Alam: Tren Gaya Hidup Slow Living Meningkat di Kalangan Generasi Muda
Jakarta, Sofund.news – Di tengah hiruk-pikuk dunia digital dan tekanan gaya hidup serba cepat, tren slow living atau gaya hidup lambat semakin mendapat tempat di hati generasi muda. Tak lagi terpaku pada produktivitas tanpa henti, banyak anak muda kini mulai melambatkan langkah, memilih kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna.
Gaya hidup slow living sejatinya bukan hal baru. Konsep ini berakar dari gerakan slow food yang dimulai di Italia pada tahun 1980-an sebagai bentuk protes terhadap budaya makanan cepat saji. Kini, filosofi “slow” merambah banyak aspek kehidupan—dari cara bekerja, bersosialisasi, hingga bagaimana seseorang meresapi waktu luang.
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan atau pencapaian. Justru, dengan melambat dan memberi ruang pada diri sendiri untuk bernapas, seseorang bisa menemukan kualitas hidup yang lebih baik. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial, tempat banyak kreator konten berbagi rutinitas harian yang sederhana namun bermakna, seperti menyeduh teh pagi-pagi, membaca buku di bawah sinar matahari, atau berkebun di halaman rumah.
Salah satu contoh nyata adalah Clara (28), seorang content creator dari Bandung yang mulai menerapkan slow living sejak 2022. “Dulu saya bangga bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam sehari, tapi selalu merasa lelah dan kosong. Sekarang, saya lebih memilih fokus pada satu aktivitas, menikmatinya, dan benar-benar hadir,” ungkapnya. Clara kini rutin membagikan video-video kesehariannya yang sederhana tapi menenangkan: memasak makanan sehat, menulis jurnal, atau jalan kaki pagi di taman kota.
Tren ini juga mulai merambah dunia desain interior dan fashion. Banyak orang mulai memilih desain rumah yang minimalis, berunsur natural, serta pakaian berbahan nyaman dan tahan lama. Brand-brand lokal pun mulai mengusung tema sustainable living, selaras dengan filosofi slow living yang menekankan kesadaran terhadap lingkungan.
Psikolog klinis, Dr. Intan Rahayu, menjelaskan bahwa gaya hidup lambat bisa memberikan banyak manfaat psikologis. “Dengan memperlambat ritme hidup, kita memberi kesempatan pada otak untuk beristirahat, memproses emosi, dan mengurangi stres. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental,” ujarnya.
Namun, menjalani slow living bukan berarti bermalas-malasan. Justru, kuncinya ada pada kualitas, bukan kuantitas. Meluangkan waktu untuk sarapan tanpa terburu-buru, berbincang dengan orang terdekat, atau sekadar menikmati langit sore bisa memberikan rasa puas yang lebih besar dibanding menyelesaikan lima tugas dalam satu jam.
Berbagai komunitas pun mulai terbentuk untuk mendukung gaya hidup ini. Di Jakarta, misalnya, terdapat komunitas “Pelan-pelan Aja” yang rutin mengadakan piknik akhir pekan, sesi yoga, dan lokakarya membuat kerajinan tangan. Semua kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk memperlambat ritme dan meningkatkan kesadaran diri.
Tren ini seakan menjadi perlawanan halus terhadap budaya hustle yang selama ini begitu diagungkan. Meskipun tak semua orang bisa langsung mengubah gaya hidupnya secara drastis, namun langkah kecil seperti mematikan notifikasi ponsel selama makan, berjalan kaki alih-alih naik kendaraan, atau tidur lebih awal sudah menjadi bagian dari perjalanan menuju slow living.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup selaras dengan ritme alami tubuh dan lingkungan, gaya hidup lambat diprediksi akan semakin populer. Terutama di era ketika burnout dan kelelahan mental menjadi masalah umum, slow living hadir sebagai oase—pengingat bahwa hidup tak harus selalu cepat untuk menjadi bermakna. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
Kembali ke Alam: Tren Gaya Hidup Slow Living Meningkat di Kalangan Generasi Muda
Jakarta, Sofund.news – Di tengah hiruk-pikuk dunia digital dan tekanan gaya hidup serba cepat, tren slow living atau gaya hidup lambat semakin mendapat tempat di hati generasi muda. Tak lagi terpaku pada produktivitas tanpa henti, banyak anak muda kini mulai melambatkan langkah, memilih kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna.
Gaya hidup slow living sejatinya bukan hal baru. Konsep ini berakar dari gerakan slow food yang dimulai di Italia pada tahun 1980-an sebagai bentuk protes terhadap budaya makanan cepat saji. Kini, filosofi “slow” merambah banyak aspek kehidupan—dari cara bekerja, bersosialisasi, hingga bagaimana seseorang meresapi waktu luang.
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesibukan atau pencapaian. Justru, dengan melambat dan memberi ruang pada diri sendiri untuk bernapas, seseorang bisa menemukan kualitas hidup yang lebih baik. Fenomena ini semakin terlihat di media sosial, tempat banyak kreator konten berbagi rutinitas harian yang sederhana namun bermakna, seperti menyeduh teh pagi-pagi, membaca buku di bawah sinar matahari, atau berkebun di halaman rumah.
Salah satu contoh nyata adalah Clara (28), seorang content creator dari Bandung yang mulai menerapkan slow living sejak 2022. “Dulu saya bangga bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam sehari, tapi selalu merasa lelah dan kosong. Sekarang, saya lebih memilih fokus pada satu aktivitas, menikmatinya, dan benar-benar hadir,” ungkapnya. Clara kini rutin membagikan video-video kesehariannya yang sederhana tapi menenangkan: memasak makanan sehat, menulis jurnal, atau jalan kaki pagi di taman kota.
Tren ini juga mulai merambah dunia desain interior dan fashion. Banyak orang mulai memilih desain rumah yang minimalis, berunsur natural, serta pakaian berbahan nyaman dan tahan lama. Brand-brand lokal pun mulai mengusung tema sustainable living, selaras dengan filosofi slow living yang menekankan kesadaran terhadap lingkungan.
Psikolog klinis, Dr. Intan Rahayu, menjelaskan bahwa gaya hidup lambat bisa memberikan banyak manfaat psikologis. “Dengan memperlambat ritme hidup, kita memberi kesempatan pada otak untuk beristirahat, memproses emosi, dan mengurangi stres. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental,” ujarnya.
Namun, menjalani slow living bukan berarti bermalas-malasan. Justru, kuncinya ada pada kualitas, bukan kuantitas. Meluangkan waktu untuk sarapan tanpa terburu-buru, berbincang dengan orang terdekat, atau sekadar menikmati langit sore bisa memberikan rasa puas yang lebih besar dibanding menyelesaikan lima tugas dalam satu jam.
Berbagai komunitas pun mulai terbentuk untuk mendukung gaya hidup ini. Di Jakarta, misalnya, terdapat komunitas “Pelan-pelan Aja” yang rutin mengadakan piknik akhir pekan, sesi yoga, dan lokakarya membuat kerajinan tangan. Semua kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk memperlambat ritme dan meningkatkan kesadaran diri.
Tren ini seakan menjadi perlawanan halus terhadap budaya hustle yang selama ini begitu diagungkan. Meskipun tak semua orang bisa langsung mengubah gaya hidupnya secara drastis, namun langkah kecil seperti mematikan notifikasi ponsel selama makan, berjalan kaki alih-alih naik kendaraan, atau tidur lebih awal sudah menjadi bagian dari perjalanan menuju slow living.
Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya hidup selaras dengan ritme alami tubuh dan lingkungan, gaya hidup lambat diprediksi akan semakin populer. Terutama di era ketika burnout dan kelelahan mental menjadi masalah umum, slow living hadir sebagai oase—pengingat bahwa hidup tak harus selalu cepat untuk menjadi bermakna. (Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)